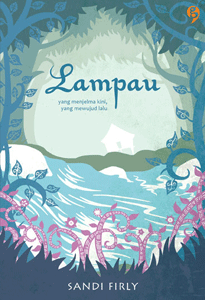6.11.14
29.9.14
Mencari "Idiot"


(Membaca Novel Galuh Hati, Randu Alamsyah)
Oleh M.
Nahdiansyah Abdi
Saya membaca novel Galuh Hati (Moka Media, Jakarta,
2014) dengan dibayangi foto penulisnya di facebook yang diapit
dua dara itu. Novel ini mampir ke rumah saya sebab rengekan isteri yang minta
dibelikan itu novel begitu terlihat olehnya sampulnya di sebuah koran lokal.
Ah, kenapa perempuan suka dengan hal-hal yang nampak kemilau? Saya diberinya
uang untuk berburu buku itu ke rumah Harie Insani Putra. Namun buku itu malah
dibeli saat ada jualan buku di depan Perpustarda Kota Banjarbaru, beberapa
waktu kemudian. Waktu beli buku itu kepergok sama Sandi Firly. Dan diam-diam saya
sedikit merasa bersalah karena tidak juga membeli dan
membaca novel Lampau yang terbit
belum lama berselang.
Di rumah, saya desak isteri saya
supaya segera membaca, biar kali ini saya berposisi sebagai pendengar saja. Saya geleng-geleng kepala karena ia membaca dari
halaman belakang.
Saya memprotes: “Apa serunya, kalau begitu!” kata saya. Tak berapa lama ia lemparkan buku itu. Ia
ketakutan. Ia merasa ngeri karena di dalamnya ada kisah pembunuhan. Ia memang
sensitif beberapa tahun belakangan ini. Sampai kemudian saya mengkhatamkan
novel Lampau-nya Sandi Firly, Galuh
Hati tetap belum tersentuh.
16.9.14
Sekaca Cempaka dan “Mati Jadi Hantu” Kebudayaan Kita
 |
| sumber foto: fb harie insani putra, Jum'at 5 September 2014 (bukan Agustus) |
(Catatan
Kecil Selepas Diskusi Novel Sekaca
Cempaka karya Nailiya Nikmah JKF)
Oleh: M. Nahdiansyah Abdi
Sebuah novel, niscaya, dapat dimasuki lewat pintu mana saja. Seorang
pembaca memiliki kecenderungan dan minat terhadap sesuatu hal, dan dengan
“sesuatu hal” itulah ia melakukan pembacaan. Barangkali demikianlah kesimpulan
dari diskusi novel Sekaca Cempaka
karya Nailiya Nikmah JKF di Aula Perpustarda Kota Banjarbaru, Jum’at malam, 6
September 2014.
Menjadi sah-sah saja ketika Dewi Alfianti mengupasnya lewat wacana-wacana
gender, yang lain menyorot lokalitasnya, atau ada beberapa peserta yang merasa
terganggu dengan label sastra Islaminya. Tentu, tak ketinggalan, ada juga
peserta yang gatal dengan soal-soal teknis. Malam itu, semua hibuk jadi satu.
Dan semua berawal dari Sekaca Cempaka. Dari sekaca cempakalah novel ini
merangkai konflik. Bunga abadi dalam botol berisi air itu telah menjadi
pertaruhan pengarang untuk menguak batin tokoh-tokohnya dan membongkar situasi
sosial yang melingkupinya. Cerita tak akan terbangun seandainya tak ada mitos
yang hadir di sekitar keberadaan sekaca cempaka. Ya, mitos. Sederhananya, ini
cerita tentang pertarungan mitos dengan rasionalitas.
8.9.14
Lampau dan Pelajaran Menulis Novel
M. Nahdiansyah Abdi

Tentu berbeda pengalaman membaca novel antara orang yang mengenal penulisnya secara pribadi dengan orang yang tidak mengenal apapun dari penulisnya kecuali hanya sekedar nama. Menyandingkan kehidupan pribadi si penulis dengan kisah dalam novel, sepertinya akan menjadi tambahan petualangan bagi orang-orang yang mengenal dekat. Pikiran dengan sendirinya akan mengelompokkan mana bagian yang merupakan imajinasi dan mana bagian yang merupakan kisah nyata. Pada kenyataannya, tak ada satu novelis pun yang luput dari menceritakan kisah dirinya. Ada lintasan-lintasan pengalaman atau persepsi yang sangat khas, yang sesekali tersembul dalam cerita, yang berasal dari kehidupan nyata si penulis. Semakin pembaca terlibat dalam kehidupan penulis, semakin tak terelakkan dorongan untuk menelisik itu. Dan jika itu diceritakan atau dituliskan, maka akan menjadi kisah tersendiri yang tak kalah menarik.
13.4.14
Merenungi Sajak, Menjaga Bumi, Merenda Keakanan
(Perbincangan melebar
atas sajak Kalimantan Selatan 2030
Kemudian, karya Micky Hidayat)
Oleh M. Nahdiansyah
Abdi
Sebuah sajak
yang marah, yang berkabar tentang kehancuran dan tragedi, apa nikmatnya?
Bagaimana cara “berdamai” dengan puisi yang gegap gempita menceritakan murka
dan amukan alam. Saya tak tahu caranya dan sebenarnya tidak terlalu ingin
menghadapi “amukan” kata-kata mengerikan dalam tubuh makhluk yang lembut
seperti puisi. Menghadapi orang-orang gangguan jiwa di rumah sakit saja sudah
repot. Tapi kalau mau ditelusuri, ada saja penyair yang mau mengolah tema
tersebut. Salah satunya adalah penyair Micky Hidayat, yang menulis puisi Kalimantan Selatan 2030 Kemudian. Puisi
tersebut dapat ditemukan di antologi “Sungai Kenangan” (ASKS IX, Banjarmasin,
2012). Konon, puisi tersebut merupakan metamorfosis dari puisi SOS Kalimantan Selatan yang terdapat
dalam kumpulan “Meditasi Rindu”.
Jika
merunut lebih awal, di era Pujangga Baru, penyair Amir Hamzah telah pula bertutur
tentang huru hara alam. Di sajak Hanya
Satu, dalam kumpulan “Nyanyi Sunyi”, si penyair bersenandung:
Timbul
niat dalam kalbumu:
Terban
hujan, ungkai badai
Terendam
karam
Runtuh
ripuk tamanmu rampak
Manusia
kecil lintang pukang
Lari
terbang jatuh duduk
Air naik
tetap terus
Tumbang
bungkar pokok purba
Teriak
riuh redam terbelam
Dalam
gagap gempita guruh
Kilau
kilat membelah gelap
Lidah
api menjulang tinggi
dst.
TERIAKAN DIAM DAN KREDO PENYEMBUHAN
Oleh M.
Nahdiansyah Abdi*
dr. IBG Dharma Putra,
MKM, demikian nama si empunya buku. Lahir di Banjar Tengah, Negara, Jembrana,
Bali, pada 1 Maret 1961. Memulai karir sebagai dokter atau kepala puskesmas (?)
di desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Nasib mengantarkannya ke berbagai
rupa-rupa jabatan, di berbagai kota di Kalimantan Selatan, hingga terakhir
menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai). Buku
Teriakan Diam diterbitkan dalam masa
itu. Namun, terhitung sejak 1 Desember 2013, ditarik ke provinsi dan diangkat menjadi
plt. Direktur RS Jiwa Sambang Lihum. Dan setelah ini, entah ke mana lagi.
Ada 44 (empat puluh
empat) puisi dalam kumpulan Teriakan Diam.
Sebagai kumpulan puisi debutan, barangkali puisi-puisinya tak terlalu istimewa.
“Aku ingin seperti Renda walau tak
sampai/Ingin pula meniru Tardji, Goenawan dan Emha/Kadang ingin jadi Taufik/Dan
sering sok Chairil Anwar, ” tuturnya dalam sajak Puisiku Sepi. Para pencari “efek kejut” dari puisi, dalam sekali
baca, barangkali tak akan menemukan apa-apa di sini. Tinimbang membincangkan
puisi, saya lebih tertarik dengan esai yang ditulisnya untuk buku ini. Judulnya
Kredo Penyembuhan.
“Puisi seharusnya punya kegunaan pragmatis di
samping makna filosofi yang dikandungnya. Tanpa hal tersebut maka puisi
hanyalah kegenitan pengisi waktu luang yang sia-sia,” tulisnya di paragraf
awal. Setelah itu, secara panjang lebar dijelaskan tentang interaksi jiwa,
badan (wadag) dan lingkungan kehidupan. Dikatakan bahwa jiwa adalah inti dan
bagian holistik dari kehidupan. Jiwa adalah abadi dalam pengembaraan filosofis
kosmis untuk mencari sumbernya. Dan dalam kehidupan, jiwa ikut ambil bagian
dalam alam kehidupan yang nyata. Pertemuan jiwa dengan domain holistik
kehidupan adalah takdir dan kenyataan, tulisnya.
KELISANAN DAN KEBERAKSARAAN, SEBUAH CATATAN*
Oleh: M. Nahdiansyah Abdi
Kita hidup dalam budaya lisan yang kental.
Kelisanan itu muncul dari pelisan, sebagai aktor utama, dan penonton, di sisi
yang berseberangan. Budaya menonton telah menjadi bagian dari hidup kita. Seni
tradisi kita hanya dipenuhi tontonan. Seni tari, seni musik, seni drama,
niscaya mensyaratkan hadirnya penonton. Madihin, mamanda, bakisah, balamut, basyair,
musik panting, aneka tarian, memiliki kegairahan dengan adanya penonton.
Jadilah ketika televisi hadir, tradisi menonton kita menemukan oasenya.
Televisi hadir 24 jam, memungkinkan kita mengatur waktu untuk memelotinya
sesuai dengan waktu lowong kita. Jangkauannya luas, melintasi berbagai ruang
dan waktu. Acara hari ini, bisa ditayang
esok hari, dan esok lagi, dan esok lagi, dan bertahun-tahun kemudian hingga
menjangkau manusia yang akan datang.
JALAN MENUJU GUMAM
Oleh M.
Nahdiansyah Abdi
Empat buku gumam telah diluncurkan oleh Ali Syamsudin Arsi
(ASA), yaitu Negeri Benang pada Sekeping
Papan (2008), Tubuh di Hutan-hutan
(2009), Istana Daun Retak (2010), dan
Bungkam Mata Gergaji (2011). Sampai saat
ini, penulisnya masih bersikukuh bahwa gumam adalah genre tersendiri, terlepas
dari beragam komentar yang memuji dan menyangsikannya. Bagi saya sendiri, hanya
ada satu pintu masuk untuk memahami gumam, yaitu kata “gumam” itu sendiri.
Orang barangkali kesulitan mengidentifikasi jenis kelamin gumam. Dikatakan
puisi bukan, dikategorikan prosa juga tak tepat. Ada orang yang melihat ciri
gumam dari kerumitan dan kemampuannya dalam jungkir balik bahasa, yang tentu, membuat
lelah pembacaan akibat abstraksi ide yang berlebihan1. Yang lain menyebut
gumam sebagai karya yang asimetri, disharmonis, dan menggambarkan adanya
dekonstruksi. Dikatakan, Gumam ASA sengaja didesain tidak teratur sebagai dasar
estetiknya2. Pernyataan-pernyataan itu barangkali benar adanya. Namun,
tak sedikit bagian dari gumam yang runtut, teratur, dan harmonis. Sepertinya
gumam ingin melanggar semua batasan-batasan yang ada. Ia bisa sangat puitis,
bila sangat prosais, namun juga bisa sangat gelap.
Langganan:
Komentar (Atom)