M. Nahdiansyah Abdi

Tentu berbeda pengalaman membaca novel antara orang yang mengenal penulisnya secara pribadi dengan orang yang tidak mengenal apapun dari penulisnya kecuali hanya sekedar nama. Menyandingkan kehidupan pribadi si penulis dengan kisah dalam novel, sepertinya akan menjadi tambahan petualangan bagi orang-orang yang mengenal dekat. Pikiran dengan sendirinya akan mengelompokkan mana bagian yang merupakan imajinasi dan mana bagian yang merupakan kisah nyata. Pada kenyataannya, tak ada satu novelis pun yang luput dari menceritakan kisah dirinya. Ada lintasan-lintasan pengalaman atau persepsi yang sangat khas, yang sesekali tersembul dalam cerita, yang berasal dari kehidupan nyata si penulis. Semakin pembaca terlibat dalam kehidupan penulis, semakin tak terelakkan dorongan untuk menelisik itu. Dan jika itu diceritakan atau dituliskan, maka akan menjadi kisah tersendiri yang tak kalah menarik.
Saya membaca novel
Lampau karya Sandi Firly saat telah banyak tulisan yang mengulasnya dan dalam
kondisi yang bisa dikatakan tak lagi hangat karena sudah lama diangkat dari
oven penerbit. Padahal itu baru setahun yang lalu. Ah, kenapa saat ini begitu
mudah “sesuatu” menjadi lampau. Mendapatkan bukunya pun dalam kondisi hati yang
tidak enak sehabis disindir habis-habisan oleh Budi Darma dalam buku Solilokui.
Katanya, sungguh mengherankan, bahwa kaum intelektual kita masih suka menerima
yang gratisan atau semacam itu. Meskipun tak layak digolongkan kaum
intelektual, saya telanjur tersinggung. Waktu menerima itu memang saat bertamu
ke rumah penulis. Ada Hajri juga. Kata Hajri, memang punya duit untuk membeli?
Saya terdiam menyadari dompet yang cekak. Membeli novel tidak ada dalam pikiran
saya, yang ada hanya buku puisi saja. Tapi sepertinya Sandi tulus. (Aha, ketemu juga
apologinya!). Paling tidak itu meredam rasa bersalah saya. Sembari mengharapkan
sesuatu yang musykil, misalnya Sandi tak pernah menemukan tulisan ini.
Lama “Lampau” tak tersentuh. Ia tetap dalam
bungkus plastiknya. Sempat terselip sesal kenapa kemarin lupa minta tanda
tangan penulisnya. Sesuatu yang kini lumrah meskipun kalau dipikir buat apa
juga. Mau membanggakan kalau sudah ketemu sama penulisnya? Tapi konon, kegiatan
kecil itu membahagiakan penulisnya juga. Kembali ke “Lampau”, ia bahkan menjadi
alas mouse buat komputer saya di
rumah. Hah? Terus terang bahannya bagus. Setidaknya ia berguna dan dengan
begitu ia akan bisa terlirik, sesekali. Ketimbang di rak buku. Tapi jurus itu
juga tak mempan. Ia tetap dalam kepompongnya berbulan-bulan. Dan akhirnya,
kesempatan itu tiba juga. Saat ini. Dan segera setelah itu, saya tak tahan
untuk tidak menulis.
Seperti kebiasaan membaca buku puisi, saya
mulai membaca dari halaman mana saja, maksudnya mana yang kebuka duluan. Dan
yang terbuka pertama adalah halaman ketika Sandayuhan di atas kereta api menuju
Jakarta, setelah pening berkapal laut dan memutuskan tidak akan pulang dalam
waktu dekat gara-gara trauma mabuk laut. Pembacaan saya tidak lama. Hanya
terbaca pengalaman si tokoh menjadi “preman” pasar, menulis dan menerbitkan
novel, berkenalan dengan Alia Makki dan terakhir bertemu dengan Ranti, teman di
masa lalu, dalam sebuah peluncuran novel. Malam itu saya memutuskan cukup
segitu saja pembacaan saya, saya ingin menulis.
Pelajaran pertama yang saya dapat, adalah
pelajaran menulis novel. Pelajarannya sederhana. Sebagaimana jalan yang
ditempuh Sandayuhan: Tuliskan pengalamanmu saja, tambahkan sedikit imajinasi. Ceritakan
hanya ceritamu di masa lalu dan setelah itu mainkan imajinasimu. Tapi ada bagian
yang mungkin akan terlewatkan bagi mereka yang bercita-cita jadi penulis, bahwa
Sandayuhan sering main ke toko buku buat membaca-baca novel. Proses ini bisa
jadi terabaikan. Sering orang punya keinginan besar menulis hal yang besar
tanpa melewati banyak proses pembacaan. Hikmah dari banyak membaca novel,
seperti kisah Sandayuhan, akan menimbulkan benih berupa ilmu perbandingan.
Dengan sendirinya akan terkotak-kotaklah para novel itu ke dalam kriteria novel
bagus atau biasa-biasa saja. Yang bagus tentu di kemudian hari akan
menginspirasi dan memberi terang jalan si pembaca, tapi yang biasa-biasa pun
bermanfaat. Setidaknya, ia membuat novel bagus jadi lebih bercahaya. Sebab,
bagaimana sesuatu dikatakan bagus kalau tidak ada pembandingnya. Kalau tidak
punya ilmu pembanding, novel jelek pun bisa dikatakan bagus.
 |
| Di Bali, sewaktu UWRF |
 |
| Waktu masih gondrong |
Ada kemiripan antara Chairil Anwar dengan
Sandi Firly, namun Si Binatang Jalang jatuhnya menulis puisi dan Si penyuka
jaket jean lusuh dan topi kupluk itu, jatuhnya menulis novel. Keduanya
petualang yang tak dapat terikat (setidaknya dimunculkan dalam sajak atau
diwakilkan pada tokoh cerita), juga menulis bertema cinta dan kematian sama
bagusnya. Lampau, dengan sendirinya, beroperasi di dua medan pengertian
sekaligus. Di satu sisi berdiri di ranah waktu, di sini lain berdiri di ranah
tempat atau ruang. Di ranah waktu, ia sejalan dengan ekor di judul Lampau: yang
menjelma kini, yang mewujud lalu. Sebagai ruang, ia menjadi sebuah tempat
terikat. Sebagai waktu, lampau melukiskan betapa tidak mudahnya lepas dari
ingatan masa lalu dan sebagai tempat, ia menjadi simbol dari perjuangan untuk
dapat mengikat diri, meski kefanaannya tak terelakkan. Walaupun kedua penulis
ini ada kemiripan, tidak lantas nasibnya juga sama. Nasib adalah kesunyian
masing-masing, tulis Chairil Anwar. Dan “kita memang tidak pernah tahu” ,
meminjam ungkapan Sandi saat menutup Lampau. Tapi setidaknya saya tahu akan
menutup tulisan ini, sekarang telah lewat dari pukul 01.00 dini hari. Dan saya
bukan makhluk nokturnal seperti dua penulis itu. Juga bukan pecinta kopi.
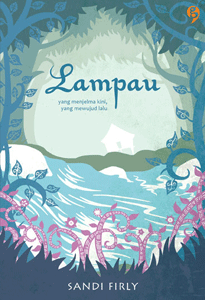



Tidak ada komentar:
Posting Komentar